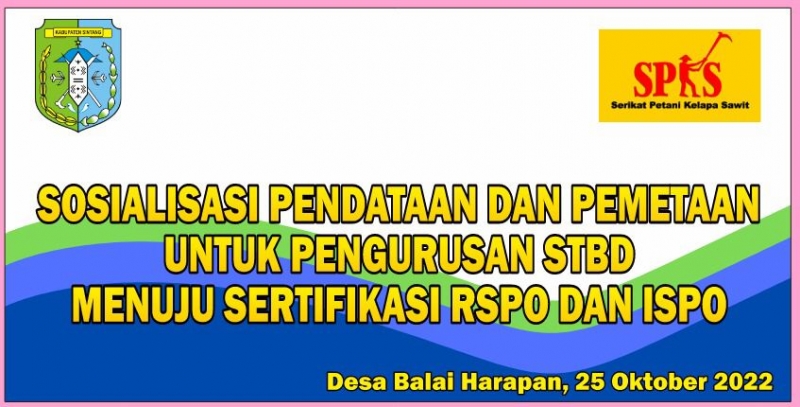Sepanjang 2018, petani sawit diakui mengalami keresahan akibat harga TBS yang turun drastis. Pengawasan Pemerintah dibutuhkan.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menjadikan Hari Tani sebagai momentum untuk menyampaikan beberapa masukan yang menjadi isu krusial menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Perijinan Sawit).
Intinya, SPKS mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secepatnya melaksankan Inpes Moratorium Perizinan Sawit. “Kepada menteri ATR-BPN dalam hal penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% dari pelepasan kawasan hutan dan dari Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit,” ujar Kepala Departeman Advokasi SPKS, Marselinus Andry melalui keterangan tertulisnya kepada hukumonline, Rabu (26/9).
Hingga saat ini, belum ada kejelasan solusi bagi perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan walaupun Presiden sudah mengeluarkan Inpres No. 8 Tahun 2018 yang dipandang sebagai landasan moratorium sawit. Ketidakjelasan itu terutama berkaitan dengan 20% yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk subyek petani, termasuk mengenai siapa yang memenuhi syarat, dimana dan berapa luasan petani kelapa sawit yang bisa dibebaskan, termasuk juga alokasi untuk petani dari HGU (Hak Guna Usaha).
Marselinus mengatakan belum ada kejelasan masa depan petani. Karena itu, ia mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati melakukan legalisasi terhadap lahan petani kelapa sawit dalam Kawasan. Perlu diwaspadai oknum yang mengaku-ngaku sebagai petani padahal bukan petani dan tidak tinggal di kawasan pedesaan.
SPKS meminta Pemerintah terlebih dahulu menetapkan definisi jelas tentang petani kelapa sawit yang akan menjadi subyek penerima manfaat. Kejelasan ini penting agar implementasi legalisasi lahan tepat sasaran, khususnya bagi lahan petani yang ada dalam kawasan hutan. Tanpa ada definisi yang jelas, sangat mungkin Inpres tidak mencapai sasaran, dan sustainability dan kesejahteraan petani di perkebunan tidak akan pernah tercapai. Kementerian ATR/BPN juga diminta untuk terbuka kepada publik terkait dengan HGU yang akan didistribusikan kepada petani, dan memperjelas besaran 20% yang dimaksud.
SPKS juga meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR-BPN untuk menjadikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) petani kelapa sawit sebagai sumber informasi/data untuk penerbitan Sertifikat Lahan. Kebijakan ini berguna untuk mempercepat proses legalisasi petani sawit serta tidak mengulangi kesalahan proses sebelumnya. SKPS mendesak Kementerian terkait untuk memperjelas skema kemitraan atau pola kerjasama antara perusahaan perkebunan dan petani plasma serta petani mandiri.
Selama ini sering terjadi konflik dalam kemitraan antara perusahaan dan petani. Konflik terjadi antara lain karena kemitraan yang tidak adil, masalah transparansi satuan pembiayaan kebun dan dokumen kredit untuk petani, luas kebun plasma yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta masalah plasma yang tidak dibangun oleh perusahaan dan perusahaan membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani dengan harga yang murah.
Konflik ini oleh SPKS dipandang sebagai akibat dari pola kemitraan manajemen satu atap. Dalam kemitraan ini petani tidak memiliki hak untuk pengelolaan dan hak atas kebun. Walaupun kebijakan moratorium hendak mempercepat pembangunan kebun plasma sebesar 20% dari luasan yang dibangun perusahaan, namun hal itu tetap belum menyentuh kebutuhan pokok petani. “Seperti alokasi untuk perusahaan masih sebesar 80% dan tidak menyentuh pola kerjasama antara kedua belah pihak,” ujar Marselinus.
Sepanjang 2018, petani sawit diduga mengalami keresahan akibat harga TBS yang turun drastis tanpa langkah berarti dari Pemerintah. SPKS mencatat, kondisi ini terjadi di seluruh wilayah perkebunan kelapa sawit hingga mencapai harga terendah, yaitu Rp500–Rp1.050 per kilogram. Ini akibat skema pembelian TBS bagi petani sawit belum diatur secara tepat untuk membangun kemitraan antara petani kelapa sawit mandiri dan perusahaan sebagai pembeli TBS. Meski ada harga pemerintah sebagai acuan, praktknya, perusahaan tetap menetapkan harga pembelian TBS di tingkat pabrik “Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pembelian yang dilakukan oleh tengkulak yang bekerja sama dengan pabrik. Saat ini, kurang lebih 32% petani mandiri menjual ke tengkulak,” tambah pejabat Departemen Komunikasi SPKS, Dian Maya Sari.
Dalam konteks ini, SPKS meminta ketegasan dan konsistensi Pemerintah agar Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit (BPDP-KS) tidak mengalokasikan dana untuk subsidi biodiesel. Subsidi biodiesel berdampak pada munculnya praktik kutipan BPDP-KS. Kutipan ini telah menurunkan harga CPO lokal yang berakibat rendahnya harga TBS hingga Rp125-150 per kilogram. Penghitungan harga TBS berdasarkan harga CPO lokal.
Subsidi biodiesel mendorong ekspansi perkebunan besar yang berakibat pada hilangnya wilayah-wilayah moratorium untuk kepentingan industri biodiesel dan mengakibatkan kelebihan suplai (oversupply). Jika terjadi oversupply, petani tidak bisa menjual TBS ke pabrik-pabrik milik perusahaan karena CPO melimpah. Hal ini diperparah dengan kondisi pemberdayaan petani dan pembenahan sektor perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh tidak berjalan akibat buruknya tata kelola BPDP-KS untuk pembangunan berkelanjutan dan rendahnya perhatian untuk pemberdayaan dan tata kelola bagi petani-petani sawit mandiri.
Sebenarnya pada awal kemunculan BPDP-KS di 2015, SPKS menyambut baik BPDP-KS. BPDP-KS dipandang dapat menjawab masalah yang dihadapi oleh petani yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Namun dalam perjalanannya, BPDP-KS dinilai hanya bekerja sekitar 2% dan hanya untuk replanting.Oleh karena itu, pada tahun 2017, SPKS sempat melayangkan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan terhadap UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. PP itu menambah tujuan penghimpunan dana. SPKS menduga ada penyelundupan hukum di situ, yakni penambahan tujuan penghimpunan dana. “Itu yang kami sebut penyelundupan hukum,” kata Marselinus.
Belum Diatur
Hingga kini, kriteria jenis lahan dan mekanisme pelepasannya kepada petani sawit belum diatur secara jelas. Ini yang mengakibatkan munculnya persoalan dalam pengalokasian 20 % kawasan hutan terus berulang. “Bagaimana mekanisme pelaksanaannya belum ada,” ujar Kepala Divisi Kebijakan Agraria di Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor, Bayu Eka Yulian.
Meskipun amanah alokasi 20% kawasan hutan kepada petani telah diatur dalam tiga rezim sektoral, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 51 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi; ada UU Perkebunan yang berada di bawah Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Guna Usaha.
Pasal 4 ayat (2A) Peraturan Menteri LHK di atas mengatur legalisasi pemenuhan kewajiban kebun masyarakat seluas 20% dari kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Jadi, selain pelepasan kawasan hutan seluas 20%, kawasan hutan yang dilepaskan tersebut harus bisa diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Menurut Bayu, 20% lahan akan dihitung berdasarkan luas kawasan yang dapat diusahakan. Ini bisa menjawab lahan seperti apa yang bisa diusahakan.
Data Pusat Studi Agraria IPB menyebutkan alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) mencapai 437 ribu hektare. Dari tujuh kriteria TORA, kriteria pertama yang disebut adalah kawasan pelepasan hutan. Masalahnya, setelah kawasan hutan dilepas, ada kesulitan menentukan luas lahan yang bisa diusahakan perkebunan karena bergantung pada karakteristik hutan. Dari jumlah yang bisa diusahakan, barulah ditentukan 20% yang akan dilepaskan kepada petani.
Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, kata Bayu, ada 167 perusahaan yang memperoleh alokasi pelepasan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut baru 41 perusahaan yang sudah mengurus HGU.
Selain itu, subjek penerima lahan masih menjadi pertanyaan. Apakah orang yang berada satu desa di kawasan hutan yang akan dilepas atau bisa dari daerah lain. Karakter demografi penduduk di sekitar kawasan hutan di Papua dan Kalimantan bisa berbeda. Menurut Bayu, Pemerintah perlu membuat spectrum prioritas penerima pelepasan kawasan hutan berdasarkan pendekatan domisili. Jika tidak ada warga masyarakat di sekitar kawasan pelepasan, maka warga luar boleh diizinkan. Untuk itu, perlu ada sinergi dengan Kementerian Desa untuk mengetahui potensi warga miskin di daerah sekitar kawasan pelepasan. Warga yang dulu tanahnya dirampas perkebunan juga bisa menjadi prioritas.
Skema prioritasnya bisa dibagi. Pertama, penduduk yang bertempat tinggal atau bermukim di sekitar kawasan alokasi 20% lahan perkebunan. Kedua, petani yang bertempat tinggal atau bersedia tinggal di desa atau kelurahan yang berbatasan dengan kawasan pelepasan. Ketiga, penduduk yang bertempat tinggal tidak di wilayah lokasi pelepasan.
Masalah lain yang perlu dipikirkan adalah batasan luas lahan yang dimiliki seorang petani. Penting untuk membatasi pembagian agar tidak terkonsentrasi di tangan satu dua orang. Selain itu, perlu dibangun kesepahaman mengenai penggunaan lahan untuk usaha sendiri, tidak ditelantarkan, dan tidak ada pengalihan ha katas lahan yang dilepaskan. Jangan sampai lahan berubah fungsi. “Untuk itu perlu program pemberdayaan,” pungkas Bayu.

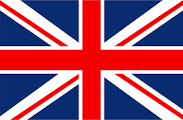 English
English Indonesia
Indonesia